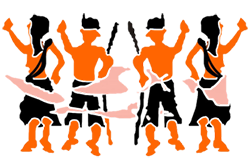Peladang Takkan Mati Terbakar Akibat Apinya Sendiri: Ladang Berpindah, Kebakaran Hutan dan Kriminalisasi
oleh Bima Satria Putra.
Berladang. Orang Dayak Ngaju menyebutnya malan. Dalam berladang, sebidang tanah hanya diolah untuk sementara, biasanya dibuka dengan dibakar, kemudian ditinggalkan dan kembali ke vegetasi alaminya. Saat ditinggal, pengolahnya akan pindah ke sebidang tanah lain untuk musim tanam berikutnya dan mungkin baru akan kembali ke bidang tanah semula beberapa tahun kemudian. Lahan yang lama dibiarkan liar, atau dipulihkan.
Terdapat kisaran waktu yang berbeda-beda tentang awal praktik ladang berpindah di Kalimantan. Sellato memperkirakan bahwa praktik perladangan berpindah yang dilakukan suku Dayak saat ini sudah ada sejak, paling tidak, dua abad yang lalu. Sementara itu, Mering menyatakan bahwa cara bercocok tanam yang beragam di berbagai wilayah di Kalimantan diketahui sudah dilakukan sejak 6000 tahun SM (Siahaya, 2015).

Ladang berpindah merupakan perwujudan dari adaptasi manusia terhadap ekosistemnya. Jika kondisi geologis Jawa membuat tanah erosi hasil vulkanik yang kaya dengan unsur hara cocok dengan jenis pertanian ekstensif seperti sawah, beda cerita dengan Kalimantan. Di sini, abu dan arang sisa membakar lahan itulah yang bermanfaat untuk menyuburkan lahan. Oleh karena itu, tidak adil untuk memandang ladang berpindah sebagai teknik pertanian yang tertinggal, tidak produktif, dan primitif. Ladang berpindah adalah kearifan lokal, tidak hanya karena menjadi ciri khas budaya dari penduduk setempat, tetapi juga kebajikan pendudukan setempat yang paling tahu tentang yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di tempat mereka sendiri.
Sayang kenyataannya tidak selalu berjalan demikian sebab kebijakan pemerintah dan kearifan lokal sering berlawanan satu sama lain. Terbutakan oleh kemilau swasembada beras tahun 80’an, pemerintahan Suharto menjalankan Mega Rice Project (MRP) yang dimulai pada tahun 1995 di Kalimantan Tengah. Saat itu, satu juta hektar sawah yang setara dengan luas dua Pulau Bali dibuka dengan mengeringkan lahan gambut. Seratus ribu transmigran dari Jawa dan Bali juga didatangkan untuk mengolah lahan yang baru dibuka tersebut. Akan tetapi, paradigma teknokratik Orde Baru terbukti terlalu pongah dan berakhir malapetaka. Tanah gambut yang miskin unsur hara terbukti terlalu keras dan tidak cocok untuk jenis penanaman padi dari Jawa-Bali. Pemerintah akhirnya menghentikan proyek tersebut dan yang tersisa adalah lahan gambut kering tandus yang setiap tahunnya terbakar dalam skala besar.
Sejak semula, pemerintah Suharto telah secara terang-terangan menyalahkan para peladang selama kebakaran lahan dan hutan besar-besaran di Kalimantan pada tahun 80’an sebagai strategi untuk mempromosikan pembukaan perkebunan yang tengah berkembang pesat (Eilenberg, 2022). Oleh karena itu, pemerintah bukannya tidak peka terhadap kearifan lokal. Ini bukan soal pengambilan kebijakan yang keliru dari para politisi. Sebaliknya, ini terjadi karena pemerintah harus melayani kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar. Karena tidak dapat mengusik kepentingan-kepentingan itu, pemerintah perlu mencari kelompok di pinggiran untuk dipinggirkan. Dalam kasus ini, korbannya adalah para peladang.
Peladang: Kambing Hitam Karhutla
Pada zaman kolonial Hindia Belanda, ladang berpindah dilarang berdasarkan peraturan tahun 1874. Penduduk desa diharuskan memperoleh izin resmi sebelum membuka hutan untuk memperluas pertanian desa (Fox, 2009). Untuk menaklukkan Dayak Iban di Kalimantan Barat yang sukar diatur, pemerintah kolonial mendesak mereka untuk turun ke dataran rendah dan membuka sawah, meski hal ini tidak bertahan lama karena sebagian besar kembali ke perbukitan untuk berladang (Eilenberg, 2022). Pada hari ini, aturan membakar ladang telah diatur dalam UU No.41/1999 tentang Kehutanan, UU No.32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.39/2014 tentang Perkebunan. Beruntungnya, banyak dari peraturan ini sebagian besar waktu tidak benar-benar ditegakkan di lapangan oleh aparat dan pemerintah lokal yang simpatik terhadap peladang.
Baru pada 2015 ketika kabut asap tebal sampai mengganggu negara-negara tetangga dan menciptakan kerugian ekonomi hingga US$16 miliar, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No. 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (selanjutnya disingkat karhutla). Pada 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah bekerja sama dengan Menteri Pertanian yang baru untuk mengakhiri praktik tebang-bakar di antara masyarakat peladang di penjuru negeri untuk mengurangi karhutla gambut (Gorbiano, 2019). Sejak itu pula, kriminalisasi semakin menjadi-jadi.
Tahun 2019 disebut sebagai “tahun terkelam peladang tradisional” karena 35 peladang dikriminalisasi (Betahita, 2019). Itu baru di Kalimantan Tengah saja. Di seluruh penjuru Kalimantan, ratusan peladang mungkin telah dikriminalisasi selama satu dekade terakhir. Kasus kriminalisasi yang mencuat telah memancing kemunculan koalisi dari aktivis gerakan agraria, lingkungan hidup dan masyarakat adat yang menggelar sejumlah demonstrasi. Ini juga membuka sejumlah diskusi tentang kebijakan pemerintah yang cenderung menyalahkan peladang sebagai penyebab karhutla. Esai ini membantah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar tersebut.
Pertama, budaya perladangan berpindah, terutama di Kalimantan, telah menjadi objek kajian dari banyak ahli sosial dan lingkungan hidup. Ada ratusan rujukan ilmiah lokal dan internasional yang melimpah sehingga tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa tahap membakar lahan dari proses berladang berpindah tradisional di Kalimantan dilakukan dengan hati-hati. Untuk memulai pembakaran lahan, para peladang selalu berkoordinasi dengan tetangga pemilik lahan lainnya. Mereka juga tidak membakar dan meninggalkan lahan begitu saja. Seringkali, mereka menginap selama beberapa hari di ladang. Karena terdapat pondok dan kebun mereka sendiri, tidak masuk akal membiarkan kebakaran jadi tak terkendali. Para peladang juga melakukan tindakan preventif seperti memperhitungkan arah angin, membuat parit, atau membersihkan pinggir ladang untuk menciptakan jarak dengan lahan lain. Proses ini dilakukan secara berkelompok dan diawasi dengan seksama untuk mencegah api meluas melebihi lahan mereka. Bagaimanapun kebakaran yang meluas akan merugikan mereka sendiri sebab hal itu dapat menghanguskan lahan tetangga dan merusak hubungan sosial. Ini juga dapat merusak kebun pohon buah dan karet, lahan keramat atau merusak lahan yang tengah diistirahatkan karena baru ditanami beberapa tahun yang lalu. Di beberapa komunitas adat, api yang menjalar dianggap hal yang memalukan dan dapat dikenai sanksi adat.
Kedua, sebagian besar kasus karhutla tidak berkaitan dengan kegiatan berladang, tetapi ekspansi perkebunan kelapa sawit. Eilenberg (2022) menunjukkan bahwa membakar lahan merupakan cara yang murah dan cepat untuk membersihkan lahan. Pembakaran lahan juga digunakan sebagai alat untuk membebaskan lebih banyak lahan melalui sistem patronase dan kolusi yang rumit. Kajiannya menunjukkan jika kebakaran menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi berbagai kalangan elit—baik pejabat pemerintah daerah yang mengatur perizinan perkebunan dan ketua kelompok tani atas kontribusi mereka terhadap pembukaan lahan, dan bagi investor kelapa sawit yang mengembangkan wilayah pasca kebakaran. Lahan yang terbakar menjadi layak investasi dan berharga mahal untuk perluasan penggunaan lahan industri karena pihak perkebunan atau calon pembeli lahan lebih tertarik terhadap lahan yang telah bersih dan dibakar ketimbang yang masih liar.
Terlihat misalnya dari data organisasi lingkungan hidup Walhi Kalimantan Tengah yang mencatat 87 total titik api sejak 1 Juni hingga 7 Agustus 2017. Rinciannya, 49 titik api berada dalam Kawasan Hutan, dengan 23 titik berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), 20 titik berada dalam Kawasan Hutan Konversi (HPK). Dari total titik api, 14 diantaranya diduga berada dalam konsesi Perkebunan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit yang tersebar di 8 kabupaten di Kalimantan Tengah.
Karena besarnya kepentingan korporasi ini, maka sulit untuk mengusik karhutla yang disengaja untuk perkebunan. Maraknya praktik politik patronase di sektor perkebunan telah memungkinkan para investor dan perusahaan kelapa sawit nasional maupun internasional nyaris kebal hukuman (Eilenberg, 2022). Kenyataannya warga sipil memang lebih rentan menjadi sasaran kriminalisasi ketimbang korporasi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah menunjukkan data Polda Kalteng dimana dari 161 kasus perorangan karhutla tahun 2019, 121 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari 20 kasus korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla tahun 2019, baru dua perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Palmindo Gemilang Kencana dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (Betahita, 2019).
Ketiga, meski ratusan peladang terus mendekam di balik jeruji besi, bencana kabut asap masih terus terjadi dan malah semakin memburuk. Dari tahun ke tahun, ada kecenderungan untuk melaporkan skala karhutla dan kabut asap ke tingkat yang justru semakin parah. Dengan mengutip data dari NASA, Mongabay (2007) melaporkan bahwa karhutla 2006 adalah yang terparah sejak 1998. Lalu dilaporkan pula dari sumber data yang sama, bahwa karhutla 2015 lebih besar sejak 2000’an (Field, 2016). Menurut data yang ditampilkan di Global Forest Watch (GFW), karhutla 2019 dikatakan lebih parah ketimbang 2016-2018 (Sakinah, 2019). Terakhir, analisis organisasi lingkungan hidup internasional Greenpeace (2023) menduga bahwa karhutla pada 2023 jauh lebih besar dan parah hingga dapat disebut sebagai “kronis” jika dibanding karhutla pada 2019. Jika trend ini berlanjut, bisa ditebak jika kebakaran yang akan datang akan jauh lebih buruk dari tahun ini. Oleh karena itu, pendekatan punitif yang menyasar masyarakat pinggiran ini toh pada akhirnya juga terbukti gagal menyelesaikan krisis lingkungan hidup.
Tingkat keparahan karhutla juga terbanding terbalik dengan jumlah peladang yang semakin menurun (ketimbang ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit yang kita amati semakin meluas). Kajian Fox (2009) menunjukkan bahwa sistem perladangan berpindah di Asia Tenggara (Cina, Laos, Thailand, Malaysia dan Indonesia) telah “berubah dan terkadang menghilang dengan kecepatan yang belum pernah dialami sebelumnya.” Meski belum ada data penurunan jumlah peladang yang pasti dan terbaru, kecenderungan ini dapat diamati di lapangan. Liputan Ahmad Arif (2022) di Kompas misalnya, melaporkan bahwa di Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah, penduduknya terakhir kali berladang pada 2015. Sementara temuan dari AMAN Kalteng (2024) di Pondok Damar, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, penduduknya terakhir kali berladang pada 2004. Keadaan yang sama terjadi pada banyak desa, dan ini baru di Kalimantan Tengah saja.
Dengan mempertimbangkan tiga alasan di atas, maka sangat tidak pantas untuk menimpakan bencana karhutla dan kabut asap semata-mata kepada para peladang. Bahkan jika seluruh peladang dipenjara dan tidak ada yang berladang untuk satu musim tanam saja, maka karhutla dan bencana kabut asap tidak serta merta berhenti, kecuali proses ekspansi perkebunan kelapa sawit yang menuntut pembukaan lahan dengan membakar itu sendiri dihentikan. Peladang takkan terbakar oleh api yang dipantiknya sendiri; api yang lebih besar dari sumber lain yang akan membumihanguskan mereka.
Jaga Kearifan Lokal, Jaga Warisan Budaya
Berladang telah membentuk pemahaman dunia dan tatanan sosial-budaya bagi sebagian besar penduduk pedalaman Kalimantan. Kegiatan gotong royong menggarap ladang satu ke ladang lain secara bergilir, misalnya, adalah wujud nyata dari keguyuban suku Dayak. Para peladang juga selalu merayakan pesta panen yang menjadi penanda tahun baru Dayak. Bahkan banyak dari ritual Dayak yang bertahan hari ini berkaitan dengan perladangan. Dengan hancurnya budaya berladang, maka hancur pula praktik gotong royong dan perayaan untuk memulai tahun yang baru. Ini yang tengah kita hadapi sekarang.
Coba dipikir-pikir: sebenarnya tidak banyak yang tersisa dari kearifan lokal yang menjadi warisan budaya Dayak. Pengecualiannya adalah bahasa tradisional, seperti bahasa Dayak Ngaju yang masih dipakai oleh 1,4 juta penuturnya di Kalimantan Tengah. Tapi jika ditinjau lebih teliti, kehancuran budaya nyaris menyeluruh dalam pilar utama kehidupan tradisional Dayak.
Kehancuran ini memang kurang disadari karena perubahan sosial tersebut berlangsung secara perlahan selama lebih dari seratus tahun terakhir. Pertama ia dimulai dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang melalui “Perjanjian” Tumbang Anoi 1894 melarang kegiatan pengayauan dan pemukiman berpindah. Pemerintah Orde Baru juga mendiskriminasi kepercayaan tradisional karena TAP MPR RI IV/MPR/1978 hanya mengakui 5 agama resmi. Di saat bersamaan, stigma terhadap rumah panjang yang kumuh dan tertinggal telah mendorong penghuninya untuk menyesuaikan diri dengan standar agenda pembangunanisme Suharto sehingga menelantarkan gaya hidup leluhur yang telah berlangsung ratusan tahun.
Pemerintah pascareformasi saat ini juga menggunakan pendekatan yang persis sama dengan pemerintah Orde Baru. Jika dulu peladang dituduh perambah hutan, sekarang dituduh pembakar lahan. Kebijakan luas untuk mengkriminalisasi pertanian ladang berpindah adalah strategi pemerintah untuk mencari kambing hitam dari bencana karhutla dan kabut asap menahun. Jadi permasalahan ini punya sifat struktural, bukan personal. Tapi langkah pemerintah sengaja mengubah permasalahan yang kompleks dan sistemik dengan menyederhanakannya sebagai masalah yang seolah disebabkan oleh masyarakat peladang. Kebijakan pemerintah memang tidak selalu bijak.
Kebudayaan berladang adalah salah satu dari kearifan lokal Dayak yang menjadi warisan masa depan yang tengah terancam. Kepunahan ini bukan hal mustahil untuk terjadi jika larangan membakar lahan dan ancaman kriminalisasi terus berlangsung, sementara pelaku utama dari sektor industri yang diuntungkan dari karhutla dari tahun ke tahun dengan bebas melenggang mengulangi perbuatannya tanpa pernah dituntut tanggung jawab.
Bahkan, tanpa larangan dan pemenjaraan, kepunahan para peladang dapat terjadi dengan cepat. Fox (2009) telah menyebutkan beberapa faktor musnahnya para peladang. Mulai dari menggolongkan para peladang sebagai kelompok etnis minoritas di dalam negara-bangsa, pembagian bentang alam menjadi hutan dan pertanian permanen, perluasan departemen kehutanan dan munculnya konservasi, pemukiman kembali, privatisasi dan komoditisasi lahan dan produksi berbasis lahan, serta perluasan infrastruktur pasar dan promosi pertanian industri. Tambah pula terjadi perubahan mata pencaharian pedesaan ke perkotaan dan perluasan pasar tenaga kerja perkotaan.
Jika demikian, maka bisa jadi yang sebelumnya berladang adalah sektor pertanian, maka kelak berladang justru menjadi sektor pariwisata karena berladang berpindah adalah hal langka. Bayangkan di masa depan para peladang yang masih tersisa hidup dalam beberapa lokasi wisata kampung adat. Mereka diperbolehkan membakar lahan karena mereka menjadi bahan tontonan eksotis: artefak masa lalu yang nyaris punah tapi masih dilestarikan, bersama dengan tari-tarian yang menghibur dan replika rumah tradisional yang tak berjiwa karena tidak sungguhan dihuni. Tujuan berladang adalah menghibur wisatawan dan bukannya mengisi lumbung pangan mereka sendiri. Akibatnya orang Dayak harus mengimpor beras dari luar. Kemungkinan, tidak ada lagi bencana karhutla sebab seluruh hutan dan lahan yang tersisa telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Biasanya, ketika kita mulai menyadari hal itu terjadi, semuanya sudah terlambat.
Daftar Pustaka
Ahmad Arif & Dionisius Reynaldo Triwibowo. “Berladang, Identitas Dayak yang Kini Terlarang.” Diakses pada 10 Oktober 2024 dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/26/malan-identitas-dayak-yang-kini-terlarang.
Betahita. “Gelombang Unjuk Rasa Bela Peladang Tradisional Terjadi di Sejumlah Daerah di Kalteng”. Diakses dari https://betahita.id/news/detail/4478/gelombang-unjuk-rasa-bela-peladang-tradisional-terjadi-di-sejumlah-daerah-di-kalteng.html.html.
Eilenberg, Michael. “The last enclosure: smoke, fire and crisis on the Indonesian forest frontier”, dalam The Journal of Peasant Studies, 49:5, 2022, hlm 969-998.
Field, Robert D., Guido R. Van der Werf, Thierry Fanin, dkk. 2016. “Indonesian fire activity and smoke pollution in 2015 show persistent nonlinear sensitivity to El Niño-induced drought.” Diakses dari: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1524888113
Fox, J., Fujita, Y., Ngidang, D. dll. “Policies, Political-Economy, and Swidden in Southeast Asia”, dalam Human Ecology, 37 (2009), hlm 305–322.
Gorbiano, Marchio Irfan. 2019. “Jokowi’s new Cabinet: Siti Nurbaya keeps post as Environment minister.” Terbit di Jakarta Post, pada 22 Oktober. Diakses dari: https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/22/jokowis-new-cabinet-siti-nurbaya-keeps-post-as-environment-minister.html.
Greenpeace. “Bagai Api dalam “Sekam” Data, Karhutla 2023”. Diakses dari: https://www.greenpeace.org/indonesia/api-dalam-data-karhutla/
Martha E. Siahaya, Thomas R. Hutauruk, Hendrik S.E.S. Aponno, Jan W. Hatulesila & Afif B. Mardhanie. “Traditional ecological knowledge on shifting cultivation and forest management in East Borneo, Indonesia” dalam International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, Volume 12, 2016 – Issue 1-2.
Mongabay. 2007. “2006 Indonesian forest fires worst since 1998”. Diakses dari: https://news.mongabay.com/2007/03/2006-indonesian-forest-fires-worst-since-1998/
Walhi. “Merdeka dari Asap, Merdeka dari Deforestasi Lawan Kejahatan Korporasi”. Diakses dari: https://www.walhi.or.id/merdeka-dari-asap-merdeka-dari-deforestasi-lawan-kejahatan-korporasi
Sakinah Ummu Haniy, Hidayah Hamzah dan Mirzha Hanifah. 2019. “Intense Forest Fires Threaten to Derail Indonesia’s Progress in Reducing Deforestation”. Diakses dari: https://www.wri.org/insights/intense-forest-fires-threaten-derail-indonesias-progress-reducing-deforestation
Bionarasi
Bima Satria Putra kelahiran Basarang, Kapuas, Kalimantan Tengah pada 4 November 1995. Lulus dari jurusan jurnalistik Fiskom Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Pernah menjadi Pemimpin Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Lentera. Beberapa buku yang telah ditulis: Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan: Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Anti-kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948) (2018), Dayak Mardaheka: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan (2021) dan Anarki di Alifuru: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Kepulauan Maluku (2024). Sekarang menjalankan penelitian independen Proyek Suku Api (PSA).
Pada akhir tahun 2024, tulisan ini memenangkan Juara 1 Lomba Esai Dispursip Kalteng di Palangka Raya, dan belum pernah diterbitkan, dan atas permintaan Penulis kepada kami sekiranya tulisan ini diterbitkan melalui website AMAN Kalteng.
Penyunting, Ferdi Kurnianto